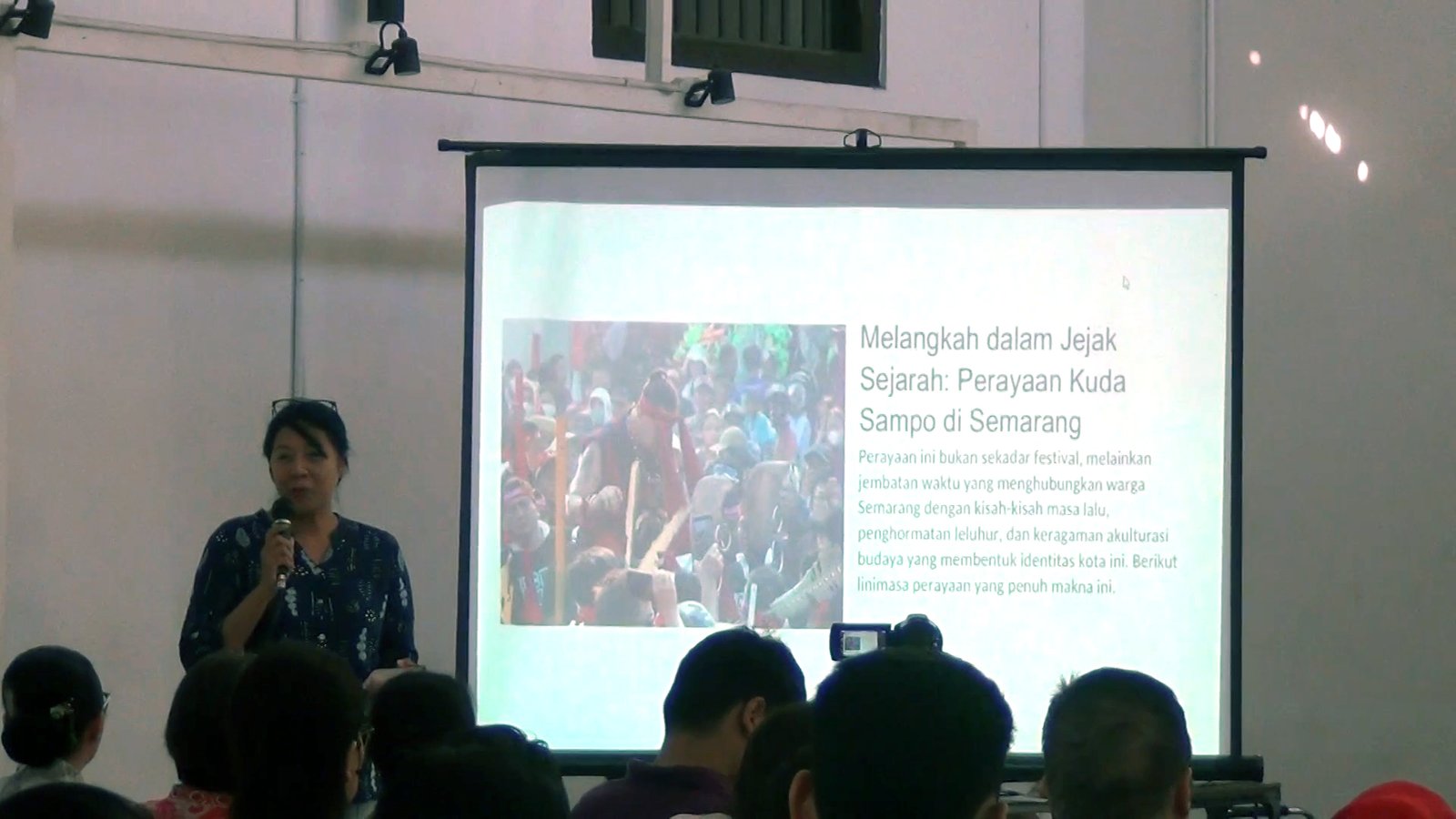SEMARANG, obyektif.tv – Semarang tidak hanya dikenal sebagai kota pelabuhan dengan sejarah panjang perdagangan dan migrasi, tetapi juga sebagai ruang pertemuan budaya yang menghasilkan tradisi unik. Salah satunya adalah arak-arakan dalam Festival Cheng Ho, sebuah prosesi multikultural yang telah menjadi warisan bersama warga kota selama lebih dari satu abad.
Peneliti dari EIN Institute, Yvonne Sibuea, mengungkapkan bahwa arak-arakan Sam Poo menyimpan jejak akulturasi yang khas Semarang. Dalam Diskusi Budaya Peranakan bertema “Festival Cheng Ho: Warisan Budaya Peranakan dalam Tradisi Multikultural di Semarang” di Gedung Oudetrap, Kota Lama Semarang, Jumat (8/8/2025), ia memaparkan bahwa prosesi ini tidak ditemukan di Tiongkok maupun kota lain di Nusantara.
“Keterlibatan kuda dalam prosesi ini adalah temuan otentik Semarang. Di Tiongkok sendiri, arak-arakan Cheng Ho tidak melibatkan kuda,” ujarnya.

Sejak dulu, arak-arakan Sam Poo diwarnai ragam atraksi budaya: tarian naga, barongsai, hingga kesenian Tatung dari Kalimantan Barat. Dalam dokumentasi koran-koran awal abad ke-20, tercatat pula kehadiran tarian tandang—mirip tayub—yang ikut memeriahkan kirab. Bagi warga, kehadiran kuda adalah simbol penting. Dulu, prosesi ini bahkan dikenal dengan nama Festival Jaran Sam Poo atau Kuda Sam Poo. Tanpa kuda, prosesi dianggap belum sah.
Jejak sejarahnya terekam sejak abad ke-19. Litografi karya seniman Jesie Rafalt tahun 1881 menggambarkan kemeriahan kirab: tandu dewa yang diusung ramai-ramai, figur naga raksasa dari kain dan kertas, dan barisan pengiring yang penuh warna. Koran De Locomotief pada 1882 mencatat arak-arakan kuda Sam Poo dari Pecinan menuju Gedung Batu, menandakan bahwa tradisi ini sudah menjadi agenda tahunan.
Tak hanya untuk memperingati Laksamana Cheng Ho, ada pula prosesi “Sam Poo kecil” yang digelar pada Mei untuk menghormati Dewa Obat Poo Seng Tay Tee. Tradisi ini lahir dari peristiwa 1860, ketika wabah kolera melanda Semarang. Setelah kimsin Dewa Obat didatangkan, wabah mereda. Sebagai ungkapan syukur, warga peranakan Tionghoa menggelar prosesi tahunan dari Pekojan menuju Boom Lama (kini dialihkan ke Pantai Marina), diiringi perpaduan musik pribumi dan Tionghoa.
Arak-arakan Sam Poo juga terekam dalam karya sastra Belanda akhir abad ke-19. Salah satu cerpen menggambarkan kelompok Bhe Kun—para pengawal kuda dan tandu Cheng Ho—yang merias wajah dengan gaya Tionghoa pada malam sebelum prosesi, lalu mengawal jalannya kirab dengan penuh pengabdian. Bagi mereka, Cheng Ho adalah sosok agung yang patut dimuliakan.

Namun, sejarah tidak selalu penuh sukacita. Pada 1906, prosesi Sam Poo diwarnai kerusuhan akibat perselisihan warga Macau terkait penjualan toapekong ke kelenteng. Konflik itu berujung korban jiwa dan memaksa aparat kolonial turun tangan. Meskipun demikian, tradisi ini tetap berlangsung dari tahun ke tahun, mengintegrasikan unsur kesenian lokal seperti tarian kandang atau lengger yang memperkaya nuansa prosesi.
“Begitu banyak narasi yang lahir dari warga Semarang sendiri. Ritual-ritual ini diciptakan, dijalankan, dan diwariskan lintas generasi. Kini, ia menjadi milik bersama, dirayakan bukan hanya oleh warga Tionghoa, tapi juga komunitas lain,” pungkas Yvonne.
Lebih dari sekadar pawai budaya, arak-arakan Sam Poo adalah cermin dari perjalanan panjang akulturasi di Semarang—pertemuan yang memadukan sejarah, seni, dan identitas kota pelabuhan ini dalam satu perayaan yang meriah dan penuh makna. ***